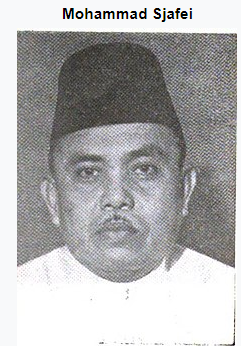PRRI: DARI REUNI MENJADI REVOLUSI
Oleh: Mursal Y
Dewasa
ini kita sering mendengar atau mungkin mengikuti kegiatan reuni. Kegiatan untuk
bertemu-temu kembali dengan teman-teman lama dan sudah cukup lama terpisahkan
oleh berbagai faktor. Apakah itu teman-teman lama sesama sekolah dulu atau
teman-teman sesama tempat kerja dan tugas pada waktu lalu. Begitu juga dengan peristiwa besar dalam
perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sebuah peristiwa besar di awal kemerdekaan
Indonesia yang kemudian dikenal dengan PRRI terjadi diawali oleh sebuah
kegiatan reuni.
PRRI,
peristiwa pergolakan daerah yang terjadi pada tahun 1958 – 1961 diawali oleh
kegiatan reuni oleh bekas anggota Devisi Banteng pada tanggal 22 Februari 1956 di Studio
Persari Jakarta. Devisi Banteng adalah satuan dari tentara yang beerjuang pada
perang kemerdekaan Indonesia di Sumatera Tengah, (Sekarang Sumatera Tengah
telah dimekarkan menjadi Propinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepri).
Devisi Banteng dibubarkan pada tahun 1948 sebagai dampak dari program RERA
(Rekontruksi dan Rasionalisasi) pemerintah waktu itu. Pemerintah di masa Kabinet
Hatta berusaha mengurangi beban ekonomi Negara terutama dalam menggaji pegawai
dan tentara. Upaya penanggulangan beban Negara ini Hatta menjalankan program
RERA merasionalisasi dan merekonstruksi jumlah dan struktur tentara. Tentara yang sebagian besar berasal dari
kalangan laskar-laskar perjuangan dan dianggap tidak profesional dikembalikan
ke pekerjaan sipil sebelumnya. RERA menjadikan militer Indonesia di isi oleh
tentara professional dan jumlah satuan dikurangi dengan membubarkan beberapa
devisi. Salah satu devisi yang dibubarkan adalah Devisi Banteng. Anggota Devisi Banteng yang lulus seleksi
dilebur atau digabungkan ke devisi lain yaitu Devisi Sliwangi.
22
Februari 1956 sejumlah bekas anggota Devisi Banteng mengadakan reuni atau
pertemuan di Studio Persari Jakarta. Reuni bertujuan untuk membicarakan nasib
sebagian bekas anggota Devisi Banteng yang hidupnya terlantar. Pembicaraan yang
semula membicara nasib teman-teman mereka yang terlantar akhirnya meluas ke
isu-isu nasional yang berkembang saat itu. Peserta reuni membicarakan dan
membahas perkembangan ekonomi dan pembangunan yang hanya tertuju untuk pulau
Jawa sementara daerah tidak tersentuh pembangunan termasuk Sumatera Tengah. Peserta reuni berkesimpulan bahwa untuk
membangun daerah Sumatera Tengah tidak mungkin menggantungkan harapan kepada
pemerintah pusat. Pembangunan Sumatera Tengah akan dilakukan sendiri dengan
cara menggali potensi dan kekayaan yang dimiliki serta menuntut otonomi yang
seluas-luasnya kepada pemerintah pusat. Pembangunan daerah akan dilakukan di
bawah koordinasi sebuah dewan yang kemudian diberi nama dengan Dewan Banteng yang diketuai oleh Letkol Ahmad Husein.

Letkol.Ahmad Husein
Dewan
Banteng menuntut kepada pemerintah pusat untuk menempatkan putra-putra daerah
terbaik menempati jabatan-jabatan penting di Sumatera Tengah. Tuntutan ini
didasarkan pada alasan bahwa putra daerah lebih mengetahui kebutuhan
daerahnya. Tuntutan ini disampaikan oleh Dewan Banteng karena pada waktu itu
jabatan-jabatan penting di daerah diisi oleh orang-orang pemerintah pusat.
Pengisian jabatan-jabatan penting di daerah oleh pemerintah pusat menurut Feit
telah menimbulkan kegusaran di daerah-daerah.
Guna
memperjuangkan tuntutanya Devisi Banteng mengutus delegasi Sumatera Tengah
untuk menemui pemerintah pusat. Delegasi Dewan Banteng beranggotakan A Hali, Dahlan
Ibrahim, Sidi Bakruddin, Kol. Dahlan Djambek, berhasil menemui Perdana Mentri
Ali Sastro Amidjojo 22 November 1956, 24 November 1956 berhasil menemui
Muhammad Hatta dan AK Pringgodigdo. Delegasi tidak berhasil menemui Presiden Soekarno,
karena presiden menyerahkan permasalahan kepada Perdana Mentri. Pada awalnya
tuntutan otonomi daerah mendapat respon baik dari pemerintah pusat, namun
kemudian tuntutan tersebut tidak bisa dipenuhi karena terjadinya peristiwa
Cikini dan pengambil alihan pemerintah di Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan
Muljohardjo oleh Dewan Banteng. Pengambil alihan pemerintah oleh Dewan Banteng
dianggap oleh pemerintah pusat sebagai bentuk tindakan inskonstitusional.
Pengambil
alihan pemerintahan yang dilakukan oleh Dewan Banteng berakibat terjadinya
ketegangan hubungan Sumatera Tengah
dengan pemerintah pusat. Pemerintah
mengirim utusan untuk menemui Dewan Banteng di Sumatera Tengah. Delegasi pemerintah pusat yang dipimpin oleh
Menteri Pertanian Eny Karim gagal menemui pimpinan Dewan Banteng. Kedatangan
romobongan Eny Karim di Bandar udara Tabing Padang disambut dengan lemparan
batu oleh masyarakat.
Sebelum
mengirim Menteri Pertanian Eny Karim pemerintah juga telah mengirim utusan ke
Sumatera Tengah di bawah pimpinan Zainal Burhanuddin. Delegasi yang dipimpin oleh Zainal
Burhanuddin memberikan laporan kepada pemerintah pusat bahwa kegiatan Dewan
Banteng tidak membahayakan stabilitas
nasional karena kegiatan Dewan Banteng lebih banyak tertuju untuk pembangunan daerah dari masalah
politik.
Ketegangan
hubungan pemerintah pusat dengan daerah Sumatera Tengah semakin menghangat
setelah sejumlah pemimpin nasional yang menyuarakan kepentingan daerah kepada
pemerintah puast bergabung dengan Dewan Banteng. Pemimpin-pemimpin nasional
yang menyuarakan kepentingan daerah antara lain M. Natsir, Sjafruddin
Prawiranegara, Burhanuddin Harahap. Para tokoh nasional tersebut bertolak ke
Padang dan bergabung dengan gerakan yang dilakukan oleh Dewan Banteng.
Keberangkatan tokoh-tokoh nasional ke Padang juga didorong karena tekanan yang mereka
terima dari pemuda-pemuda radikal atas sikap mereka yang tidak setuju dengan
tindakan pemerintah mengambil alih sejumlah perusahaan asing.
Bergabungnya sejumlah tokoh nasional yang
notabenenya tokoh-tokoh politik Islam dengan Dewan Banteng membuat gerakan
Dewan Banteng menjadi lebih revolusioner.
Pada tanggal 10 Februari 1958 dalam sebuah rapat raksasa di Padang,
ketua Dewan Banteng, Ahmad Husein menyampaikan ultimatum kepada pemerintah
pusat. Ultimatum yang disampaikan Dewan Banteng adalah:
1.
Dalam waktu 5 X 24 Jam Kabinet Djuanda harus
menyerahkan jabatanya kepada prisiden atau pejabat presiden, presiden atau
pejabat presiden mencabut mandat kabinet Djuanda
2.
Presiden atau pejabat presiden memberi tugas
kepada Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubowono IX untuk membentuk zaken cabinet
terdiri dari tokoh-tokoh yang jujur, berwibawa, cakap, cerdas dan bebas dari
anasir antituhan
3.
Meminta kepada Drs. Muhammad Hatta dan Sri
Sultan Hamengkubowono IX untuk menyediakan diri menolong Negara dan bangsa
4.
Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan
pimpinan lainnya untuk mengizinkan Muh. Hatta dan Sri Sultan Hamengkubowono IX
menyelamatkan bangsa dan Negara
5.
Meminta kepada presiden untuk kembali kepada
kedudukanya sebagai presiden konstitusi dengan membuktikanya dengan kata-kata
dan perbuatan dan memberi kesempatan sepenuhnya kepada Muh. Hatta dan Sri Sultan
Hamengkubowono IX untuk melakukan kewajibanya sampai pemilihan umum mendatang
Ultimatum
Dewan Banteng dibahas pada siding cabinet
11 Februari 1958. Sidang yang dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda menolak
semua tuntutan Dewan Banteng. Sebagai tindak lanjut dari sidang kabinet Markas
Besar Angkatan Darat memberhentikan dengan tidak hormat Dahlan Djambek, Lubis
dan Simbolon dari militer. Pemberhentian dengan tidak hormat ini juga diikuti
keluarnya surat perintah penangkapan kepada mereka dari Panglima TNI, Jenderal
AH Nasution 12 Februari 1958. Tanggapan
pemerintah pusat terhadap ultimatum Dewan Banteng dijawab oleh Dewan Banteng
dengan mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
(PRRI) 15 Februari 1958 di Bukittinggi. Dewan Banteng juga mengumumkan
Sjafruddin Prawuranegara sebagai Perdana Menteri PRRI.
Pengumuman
berdirinya PRRI mendapat sambutan dan dukungan dari rakyat Sumatera Tengah.
Dukungan yang diberikan oleh masyarakat ini tidak terlepas dari kekecewaan
mereka terhadap pemerintah pusat yang mengabaikan pembangunan dan ekonomi
daerah selama ini. Pengumuman beridirnya
PRRI ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan mengeluarkan surat perintah
penangkapan tokoh-tokoh yang terlibat PRRI pada tanggal 16 Februari 1958. Keluarnya surat perintah penangkapan
tokoh-tokoh PRRI 16 Februari 1958 menandai bangsa Indonesia mulai berada dalam
kancah perang saudara. Perang antara pemerintah pusat dengan daerah Sumatera Tengah.
Pemerintah pusat mengirim pasukan militer ke Sumatera Tengah untuk menumpas
PRRI.
Perang
saudara dalam usaha memadamkan PRRI memakan waktu yang cukup lama dan korban baik
jiwa, moril, sosial dan materil yang cukup banyak. Pemberontakan PRRI diakhiri
dengan keluarnya amnesti umum oleh pemerintah pusat bagi mereka yang terlibat.
Para tokoh yang terlibat dengan PRRI diminta untuk kembali kepada ibupertiwi dan
mereka diberi amnesti dan tidak dilakukan tindakan.
Demkian
tulisan pendek ini,
Tulisan
berikutnya saya akan coba membahas tentang kondisi sosial masyarakat Sumatera
Tengah, khususnya Minangkabau di masa perang saudara, PRRI